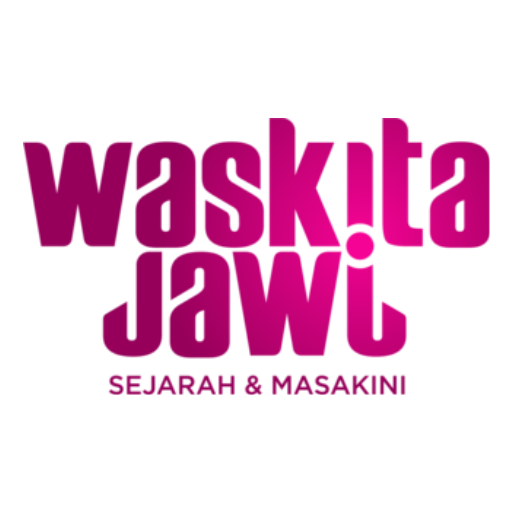Sejarah Soto : Jejak Kuliner & Kosmopolitanisme Jawa
Sejarah Soto | Selama ini sejarah dipandang sebagai kawasan rangkaian peristiwa kronologis berskala luas (makro), seperti sejarah yang kaitannya dengan politik, agama, ekonomi, dan sosial-kebudayaan; dan sedikit yang membuka pandangan ke kawasan yang lebih sempit (mikro) seperti relasi keluarga dan kuliner. Makanan mungkin ditempatkan oleh “sejarah” hanya sebagai objek ekspresionis bisu dan non-tragedi belaka, tanpa mampu menunjukkan maknanya. Namun pada era 1960-1970 upaya mengkaji studi makanan (food studies) mulai mendapatkan perhatian oleh para sejarawan dan sosiolog Perancis. Makanan dalam realitas sejarah diinterpretasikan sebagai refleksi atas tradisi masyarakat, sistem nilai serta bentuk-bentuk institusional interaksi sekaligus identitas sosial. Sebagaimana diungkapkan oleh Flandrin & Montanari (1996);
“Cette nouvelle historie n’est plus “petite”; au contrarie, elle ambitionne de toucher à tous les aspects de l’action et de la pensée humanies”
Artinya: (sejarah makanan tidak lagi sebagai hal “kecil”; sebaliknya, ia bertujuan untuk menyentuh semua aspek tindakan dan pemikiran manusia).
Lebih jauh lagi Higman (2012) memandang “makanan menentukan sejarah”, sebab dua aspek. Pertama, sejarah makanan itu sendiri, yang tidak jarang identik dengan perayaan penyajian dan perilaku konsumsi makanan itu sendiri; dan kedua, kesalinghubungan sejarah sosial dan ekonomi dalam sejarah makanan, termasuk di dalamnya perubahan-perubahan (inovasi) bentuk kuliner. Salah satu sejarawan yang menunjukkan minatnya pada makanan sebagai kajian historiografi adalah Onghokham, seperti tampak pada artikelnya “Rijsttafel: Jamuan Makan Warisan Zaman Kolonial” (1996) dan “Tempe: Sumbangan Jawa untuk Dunia” (2000). Onghokham dianggap sebagai peletak dasar sejarah makanan modern di Indonesia. Eksplorasi kajian sejarah makanan berlanjut misalnya oleh tulisan Fadly Rahman, “Rijsttafel: Budaya Kuliner Masa Kolonial 1870-1942” (2011) dan karya kolaboratif Wahjudi Pantja Sunjata, Sumarno, dan Titi Mumfangati, “Kuliner Jawa dalam Serat Centhini” (2014).
Salah satu olahan kuliner yang populer dan pas dengan ‘lidah rakyat’ adalah soto. Masakan berkuah ini dapat dikatakan memuat sejarah yang akulturatif. Lombard dalam bukunya “Nusa Jawa Silang Budaya” jilid 2 (2000), menyatakan soto berasal dari kata ‘saoto’, derivasi dialek Hokkian (Tionghoa), ‘Cau do’ atau ‘Jao To’ atau ‘Chau Tu’ (rerumputan/jeroan berempah), yang telah dikenal luas di wilayah Semarang sekitar abad 19 M. Sebagian menyatakan berasal dari kata ‘Sau Tu’, yang berarti ‘memasak jeroan’. Kemiripan masakan soto juga ditemukan pada masakan sup unggas (kimlo) di daerah Asia Tenggara, seperti di Champa dan Khmer. Sementara di India selatan (Sri Lanka) juga terdapat sup kare ringan yang disebut ‘sothi/sodhi’–diambil dari nama daun ‘sodi’ yang menjadi salah satu bahan baku kuliner ini–, yang lebih mirip ke arah sayur lodeh dan gulai di Jawa. Secara linguistik, kata ‘soto’ lebih dekat pada ‘jaoto/coto’ daripada ‘sodi/sochi/soji’ yang telah mengalami perubahan fonem nonmorfologis dan kemudian mengalami eufemisme (pengganti ungkapan secara halus) menjadi ‘soto’.
Berdasarkan hukum evolusi, yang menyatakan bahwa sesuatu yang kompleks dibentuk pada awalnya dari yang paling sederhana. Olahan masakan daging berkuah setidaknya sudah dikenal di Jawa pada abad ke-8 M, yang dimuat pada Kakawin Ramayana (era Rakai Watukura Dyah Balitung sekitar tahun 870 M). Masakan gulai telah disebut dalam adikakawin ini, khususnya pada syair (Sarggah) ke-26, bait ke-25 berikut: “…wirasā ya rasāna wanèh nya baniṅ nya lawar-lawaranya gulay-gulayanya lêmêṅ-lêmêṅanya pêṅêt-pêṅêtanya hasêm-hasêmanya…” (…ambillah juga hidangan daging kura-lura, semua jenis lawar (hidangan yang disiapkan dari darah), semua jenis gulai (sup daging), semua jenis hidangan yang disiapkan dari bambu, semua jenis pêṅêt, semua jenis hidangan asam,…). Penggunaan nasi dalam upacara keagamaan muncul pertama kali pada Prasasti Taji (823 Saka atau 901 Masehi)–ditemukan di Dusun Taji, Desa Gelang Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dalam bentuk lempengan (tamra) tembaga, sehingga dikenal sebagai ‘koperplaten van Ponorogo’–dengan istilah skul dinyun. Sementara dalam Prasasti Jrujru (852 Saka atau 930 Masehi) yang ditemukan di Malang, yang berisi penyerahan wilayah perdikan suci (dharmmakṣetra) dari Pu Sindok (çrī mahāraja çrī īçānawikrama dharmmotunggadewa) kepada penguasa Jrujru (wanua i jrujru), menyebut makanan sejenis dendeng ikan asin, olahan sup sejenis ikan, udang dan telur ([tidak terbaca] …. ḍeng hasin ḍeng …. ra slar capaca pa rumahan hurang bilulung halahala hantiga inari).
Pada era Kediri muncul kuliner sejenis sup daging pekat yang disebut ‘rarawwan’ termuat pada Kakawin Bhomākawya (81:37) gubahan Mpu Dharmaja (sekitar tahun 1182 – 1185 M). Rarawwan atau rawon dengan ciri khas keluwaknya disebut makanan bagi rakyat jelata. Sementara pada era Majapahit, catatan terkait masakan beserta pantangannya dimuat pada Kakawin Nagarakrtagama (89-90:5) gubahan Mpu Prapanca (1365 M) secara panjang:
“lwirni taḍaḥnira meṣa mahiṣa wihaga mṛga wӧk/ maḍupā, mīṇa lawan tikaṅ aṇdah ajariṅ aji lokapurāṇa tinūt, çwāna kara krimi mūṣika hilahila len/ wiyuṅ ṅalpa dahat, çatrw awamāna hurip/ kṣaya cala nika rakwa yadi purugên// prāptaṅ bhojana makadon rikaṅ wwaṅ akweḥ, saṅkêp sarwwarājatha bhojananya çobhā, matsyāsaṅkya sahana riṅ darat/ mwaṅ i wwai, rāpṛp/ drāk/ rumawuh anūt kramānuwartta//”
Artinya: (santapan terdiri dari daging kambing, kerbau, burung, rusa, madu, ikan, telur, domba, menurut agama adat dari zaman purba makanan pantangannya daging anjing, cacing, tikus, keledai dan katak. Jika dilanggar mengakibatkan hinaan musuh, mati dan noda. Dihidangkan santapan untuk orang banyak, makanan serba banyak serba sedap, berbagai ikan laut dan ikan darat. Berderap cepat datang menurut acara).
Kembali ke soto, etimologi ‘soto/saoto/jaoto’ yang telah melalui perubahan dari dialek Cina memberikan peluang asumsi bahwa masakan itu pada awalnya mungkin dibawa oleh para pedagang Cina dari Kanton–bandingkan dengan migrasi sebagian muslim Champa pada rentang waktu antara 1446–1470 Masehi, termasuk tokoh Ali Rahmat (Sunan Ampel)–yang telah memeluk Islam. Groeneveldt (1876) menulis bahwa berdasarkan catatan Ma Huan, seorang juru tulis armada Zheng He (Cheng Ho) pada pelayarannya awal abad ke-15, bahwa orang-orang dari Kanton, Zhangzhou dan Quanzhou yang telah meninggalkan Cina dan menetap di pelabuhan-pelabuhan Pesisir sebelah timur, di Surabaya, Gresik dan Tuban merupakan sebagian besar dari penduduk yang menurut taksiran mencapai seribu keluarga lebih sedikit. Menurut Ma Huan, “Di negeri ini (Jawa) ada tiga macam orang; pertama orang Muslim (huihui ren) yang berasal dari berbagai negeri di Barat, yang telah datang untuk berdagang di tempat itu; cara berpakaian, makanan mereka dan segala sesuatunya sangat pantas. Lalu ada orang Cina (Tang ren), dari Guangdong, Zhangzhou, Quanzhou atau tempat lain, yang telah melarikan diri untuk menetap di tempat itu; makanan dan adat-istiadat mereka juga sangat layak, banyak di antara mereka telah memeluk Islam dan taat menjalankan aturan-aturan agama serta berpuasa; dan yang terakhir adalah orang pribumi, mereka sangat kumuh dan kasar, dengan rambut yang berantakan dan telanjang kaki dan masih menyembah roh.”
Secara umum, bumbu soto yang kaya akan rempah, bawang putih dengan atau tanpa irisan kentang tipis-tipis yang digoreng kering, irisan telur, soun/bihun, taburan kecambah/tauge, bawang merah goreng dan irisan kubis, sebagian menggunakan taburan koya (bubuk kedelai), serta dengan atau tanpa santan (beningan). Sedangkan unsur pelengkapnya, misalnya irisan daun seledri, yang menurut Reid (2014) diperkirakan hadir di Jawa bersamaan dengan datangnya Eropa (Portugis dan Belanda) pada abad ke-16–17. Adapun lauk tambahan berupa perkedel berasal dari kata ‘frikkadel’, yang menurut van Dorp (1866) kata serapan Belanda yang diambil dari bahasa Perancis, serta berbagai daging dan jeroan yang dimasak. Berbagai jenis varian soto dapat ditemukan di berbagai kota pesisir utara Jawa, seperti Soto Madura (Sumenep) dengan bumbu rempahnya yang kuat pada daging serta kuahnya yang ringan; Soto Lamongan dengan aneka macam jeroan dengan ciri khas kaldu dari lemak sapi dan koyanya dari remahan krupuk udang dan sebagian menggunakan kecap asin dan taburan bawang putih; Soto Kudus dengan ciri khasnya daging kerbau sebagai pengganti daging sapi yang dikultuskan dengan bumbu ketumbarnya serta kuning-kunyitnya; dan Soto Betawi atau Cirebonan yang bumbunya cenderung ke Arab-Persia dengan kapulaganya serta taburan emping mlinjonya. Berbeda dengan varian soto pedalaman Jawa dengan ‘gagrak beningan’ atau tanpa santannya dengan berbagai ‘sundukan’ seperti Soto Boyolali, Solo, Sukoharjo yang tidak jarang tanpa bihun sebagai bentuk resistensi (perlawanan) atas budaya Cina. Ada soto kambangan, soto bebek khas Klaten yang konon berkaitan dengan para penyiar Islam Kajoran dan Tembayat.
Soto juga sebagian mengalami hibridisasi atau pembauran persilangan budaya, seperti Soto Ponorogo yang memadukan ciri khas soto pedalaman dengan kuah ‘komoh’ yang ringan serta kubisnya dengan paduan bumbu pesisiran (Semarang, Kendal) yang ciri khasnya menggunakan bihun. Akulturasi Soto Ponorogo tersebut dimungkinkan sudah berlangsung pada masa Lembu Kanigara atau Bathara Katong (w. 1506), Adipati pertama Ponorogo. Salah satu istrinya (garwa padmi) berasal dari daerah Lepentangi/Kaliwungu (Kendal) dan dari daerah Bagelen (Purworejo), yang dari keduanyalah dimungkinkan resep olahan masakan tersebut berasal, sebab memori kolektif terbentuk dari memori individu yang telah melalui perkembangan. Bisa jadi juga kebudayaan pesisir berupa masakan (soto) yang berpenetrasi di Ponorogo mendapat pengaruh dari para pengikut dari Tembayat–Sunan Pandanaran (w. 1547), dan Cirebon–Sunan Gunung Jati (w. 1570) yang telah berinteraksi dengan masyarakat Ponorogo pada rentangan waktu era Adipati ke-2, Panembahan Agung (1510-1520?)–disamping bukti salah satu putri Bathara Katong diperistri oleh Pangeran Sumendhe, putra Sunan Tembayat–sampai pada era Adipati ke-5, Pangeran Sepuh (1560-1580?), yang konon setelah mendirikan Masjid Kauman (Kota Lama) menempatkan posisi strategis imam masjid (pengulu) pada pendatang dari Cirebon
Sisi persilangan budaya mulai dari Cina, Arab-Persia, India, Eropa dan Jawa Kuno itu sendirilah yang menyebabkan soto dapat dikatakan sebagai kuliner kosmopolitan, yang menyatukan keragaman warisan cita rasa dunia dalam satu hidangan. Mari ‘nyoto’ kak !
.
.
.
Sumber :
- Jean-Louis Flandrin & Massimo Montanari, Historie de l’allimentation (Paris: Fayard, 1996).
- B.W. Higman, How Food Made History (Oxford: Wiley-Blackwell, 2012).
- Anthony Reid, Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680, Jilid I: Tanah di Bawah Angin, terj. Mochtar Pabotinggi (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya. Kajian Sejarah Terpadu. Bagian II: Jaringan Asia, terj. Winarsih Partaningrat Arifin, Rahayu S. Hidayat dan Nini Hidayati Yusuf (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Soewito Santoso, Ramayana Kakawin, vol. 3 (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1980).
- D.A. Rinkes, Nine Saints of Java, trans. H.M. Froger (Kuala Lumpur: Malaysian Sociological Research Institute, 1996).
- Theodore G. Th. Pigeaud, Java in The 14th Century: a Study in Cultural History. The Nāgara-Kĕrtāgama by Rakawi Prapañca of Majapahit, 1365 A.D., vol. 1 (‘S-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1960).
- W.P. Groeneveldt, Notes on the Malay Archipelago and Malacca. Compiled from Chinese Sources (‘S-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1876).
- J.L.A. Brandes & N.J. Krom, Oud-Javaansche Oorkonden. Nagelaten Transscripties (‘S-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1913).
Simak juga video kami di channel Waskita Jawi